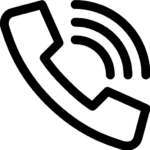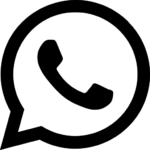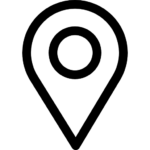Karya Sastra di Era 1990-an hingga Kini: Kumpulan Tulisan-tulisan Berkarakter

Jika kita membaca karya-karya sastra di era 1990-an hingga saat ini, kentara jelas pemikiran intelektual asing begitu dominan dalam khazanah kesusastraan Indonesia. Tidak sedikit kaidah bahasa Indonesia yang melenceng, yang kemudian mengimbas pula ke arah pemelencengan bahasa Inggris dan Arab sebagai serapan paling dominan dalam bahasa kita. Hal tersebut, disebabkan komunikasi dengan perangkat bahasa cenderung memiliki logika universal yang sekaligus menyangkut kesepakatan nalar dan akal budi suatu bangsa.
Kita berhak untuk merasa jengkel dan marah (righteous indignation) dengan maraknya gaya berbahasa yang terus mengembangkan mentalitas inlander, yang menurut Presiden Jokowi merupakan “DNA kaum terjajah”. Sepantasnya kita merasa terpanggil untuk turut-serta membangkitkan kesadaran berbahasa dan berbangsa, mengingat cikal-bakal bahasa kita (Melayu Tinggi dan Melayu Pasar) begitu sarat dengan nuansa magis dan spiritualis.
Perkembangan bahasa kita tak bisa dilepaskan dari peran ilahi dan anugerah agung yang diberikan untuk bangsa ini. Kemerosotan karakter dan akal budi tercermin jelas dari pemakaian bahasa yang kopong makna, dangkal penafsiran, seakan telah terpelanting dari akar bahasa Melayu sebagai modal utama kebangkitan bangsa ini. Bahasa Melayu Tinggi yang dipakai oleh bapak bangsa Soekarno tercermin jelas, baik melalui artikel maupun pidato-pidatonya yang begitu tangkas dan kreatif menyuarakan anti feodalisme dan segala bentuk penjajahan. Kita merasakan adanya kesenyawaan bila mencermati artikel-artikel yang ditulis Hatta, Tan Malaka, Sjahrir dan seterusnya.
Berkat perjuangan dan produktivitas karya-karya Hamzah Fansuri di abad ke-17 lalu, melalui berbagai karya puisi dan prosanya yang berbahasa Melayu, kemudian terus berkembang dipakai untuk bahasa perdagangan, pemerintahan, dan pengantar ilmu pengetahuan hingga saat ini. Hamzah Fansuri maupun Raja Ali Hadji banyak meninggalkan jejak karya-karya besar di bidang kesusastraan, baik berbentuk prosa maupun puisi-puisi sufistik. Mereka boleh dibilang sebagai perintis dan peletak dasar kesusastraan Melayu. Melalui karya-karya yang dilahirkannya, bahasa Melayu kelak menjadi bahasa nomor empat sebagai pengantar pendidikan Islam di seluruh dunia, setelah bahasa Arab, Turki, dan Persia.
Terkait dengan itu, Profesor AA Teew (1979) menegaskan kuatnya daya tarik bahasa Melayu dari berbagai pengguna bahasa di seluruh wilayah Nusantara. Pernyataan Teew ini bisa diperkuat oleh kesaksian Pramoedya Ananta Toer, Sutan Takdir Alisjahbana hingga Ki Hadjar Dewantoro. Selain itu, Teeuw juga pernah menyatakan, bahwa dari ujung barat ke ujung timur Nusantara, sesungguhnya bahasa Melayu merupakan bahasa orang-orang terdidik.
Baik Alquran maupun Injil, pada akhirnya harus mengakui bahasa Melayu sebagai patokan untuk penerjemahan resmi bagi masyarakat Nusantara. Sejak era abad ke-18 lalu, bahasa Melayu telah tumbuh subur dan terjalin erat dengan tren Islam kosmopolitan yang terbuka, toleran, egaliter dan merangkul semua pihak.
Perkembangan bahasa Indonesia pada dekade-dekade terakhir, kentara jelas melalui praktik-praktik opini dan wacana berkat persenyawaan antara kaum religius, humanis hingga kaum nasionalis sekuler. Wacana-wacana pergerakan nasional (terutama Soekarno, Sjahrir dan Hatta) saling bersatu berkelindan menyuarakan revolusi, serta saling memperkuat daya ekspresi karakter dan akal budi bangsa.
Namun, dari semua peregerakan bahasa itu, pada akhirnya semua mengakui bahwa sosok Soekarno-lah yang memiliki kekayaan referensi dalam berbagai multibahasa dan perbendaharaan ilmu yang menuntut semuanya untuk mencerna dan menganalisis. Penguasaan bahasa Arab yang dikombinasi dengan Melayu Tinggi, menjadi dua kekuatan yang mengimbangi peran bahasa Inggris dan Belanda pada masa itu.
Kita pun bisa membaca karya-karya Eka Kurniawan, A.S. Laksana, Hafis Azhari hingga Leila Chudori, nampak kentara seakan mereka berselancar di tengah arus gelombang pemikiran yang penuh dinamika dan kejutan kejutan. Mereka pun mendapati bahaya dan peluang, namun tungkai-tungkai bahasa Melayu, yang kemudian mengejawantah dalam dialek Jakarta semakin bertumbuh kuat. Menurut Hafis Azhari, fenomena itu tak lain merupakan “keniscayaan sejarah”, dan bukan semata-mata eksperimentasi bahasa belaka.
Bercermin pada Soekarno, yang sejak muda pandai mencari dan menampilkan ungkapan-ungkapan orisinal tercerahkan. Dengan “kesombongan” yang memang pantas ditunjukkan bagi perlawanan terhadap kaum penjajah, dalam tulisannya sebagai eksil di Ende, Soekarno pernah menulis: “Artikel-artikel saya memang terang-terangan mengandung jiwa Soekarno, paham Soekarno, bahkan cara berpikirnya Soekarno. Pemihakan dan pertentangan saya jelas tercermin dalam artikel-artikel itu. Kalau tidak begitu, maka artikel-artikel saya akan menjadi tulisan yang tanpa jiwa, kopong karakter. Dan dari semua kegagalan dalam karya dan kepenulisan, sesungguhnya kopong karakter itulah yang paling saya takuti.”
Ungkapan Soekarno tersebut jelas mengacu dari urgensinya keseimbangan dalam teladan hidup Rasulullah, agar adanya kesenyawaan antara hadis ucapan (qauliyah), perbuatan (fi’liyah) dan tindakan (amaliyah). Di situ jelas mengisyaratkan pola berbahasa yang kaya karakter dan penjiwaan, bukan bahasa feodalisme dan mental inlander yang semakin mencerabut solidaritas dan kesetiakawanan sosial.
Dari perspektif lain, kita tak boleh mengingkari peran pendahulu kita, selaku pelopor dan perintis kebangkitan bahasa, yang selevel dengan kinerja generasi Soekarno-Hatta, di antaranya Muhammad Yamin, Yus Badudu, hingga Anton Moeliono. Selain itu, juga para pejuang pergerakan yang terjun di bidang penerbitan harian maupun majalah, seperti Daoelat Rakjat, Pandji Islam, Suluh Indonesia Muda, hingga Fikiran Ra’jat. Kita pun mengenal peran Balai Poestaka, sebagai pelopor yang memicu terjadinya demam literasi ke lapis-lapis generasi muda pada zamannya.
Balai Peostaka dan media-media turunannya tidak bergerak di wilayah dokumentasi yang hanya sibuk dengan tumpukan berita dan timbunan informasi belaka. Dalam kajian Rolf Dobelli melalui bukunya “Stop Membaca Berita” (2021) dapat dibuktikan bahwa salah satu yang menyebabkan tumpulnya imajinasi dan pikiran manusia disebabkan maraknya tumpukan berita dalam otak kita. Media yang menyuguhkan informasi seakan hanya berfungsi sebagai cemilan yang banyak mengandung kadar gula dan pewarna, sehingga tak bisa menuntaskan rasa lapar kita terhadap ilmu. Media yang kebak berita-berita jelas akan berbeda fungsinya ketimbang buku atau artikel-artikel berdasarkan analisis dan penelitian yang mendalam.
Dengan maraknya wacana dan artikel yang mumpuni menjelang era kemerdekaan RI, para bapak bangsa kita secara serentak memeriahkan kemahiran berbahasa Indonesia, yang tak lepas dari akar Melayu, kemudian menggelorakan kesepakatannya secara masif di era 1928 pada hari Sumpah Pemuda. Upaya-upaya itu diniscayakan lantaran semua pihak sama-sama menjunjung-tinggi prinsip kemerdekaan dan kesetaraan dalam berbahasa, berbangsa dan bertanah air.
Untuk itu, menjelmalah komunitas karakter lintas suku dan ras, bahkan lintas agama dan ideologi yang menciptakan benteng pengamannya sendiri. Dalam kumpulan artikelnya, Di Bawah Bendera Revolusi, memang tak bisa dimungkiri, bahwa figur Soekarno seakan hadiah dan hidayah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia, baik dalam teladan berbahasa dan berkarakter sebagai bangsa merdeka, yang terbebas dari segala bentuk penjajahan.***
Desain Rumah Kabin
Rumah Kabin Kontena
Harga Rumah Kabin
Kos Rumah Kontena
Rumah Kabin 2 Tingkat
Rumah Kabin Panas
Rumah Kabin Murah
Sewa Rumah Kabin
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin
Source link