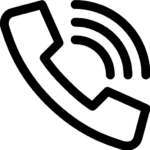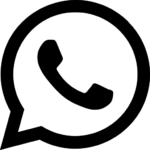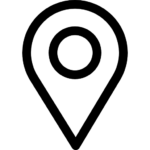Sastra dalam Fikih Islam, Halal atau Haram?

Pendahuluan
Sastra telah berkembang jauh sebelum definisi sastra itu sendiri muncul. Pada awal munculnya, sastra memuat esensi-esensi dan nilai ajaran pokok ketuhanan dan kemanusiaan. Sastra tidak hanya memuat unsur estetika di dalamnya. Perlu diketahui bahwa sastra pada mulanya merupakan satu sarana untuk mengangkat harkat dan martabat suatu golongan atau sekte.
Dalam perkembangannya sastra mengalami perkembangan dari segi substansi maupun bentuk narasi. Hingga pada masa Islam datang, yang dibawa oleh Rasulullah Saw, sastra menjadi asing, khususnya di tanah Arab. Secara tekstual, terdapat ayat-ayat Al-Qur’an yang mencela sastra dan sastrawan pada masa itu.
Hal ini menjadi pergejolakan pada masa nubuwah tersebut, sehingga terdapat beberapa kalangan yang mengharamkan sastra dengan argumentasi dalil al-Qur’an dan Hadits. Lantas, apakah pengharaman sastra dilegitimasi oleh konstruksi fikih Islam? Sedangkan masih banyak para sastrawan degan karyanya bermunculan hingga masa sekarang? hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.
Definisi Sastra
Dalam kamus besar bahasa indonesia, sastra diartikan dengan karya tulis yang bila dibandingkan dengan tulisan lain. Ciri-ciri keunggulan, seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya, akan lebih indah dan tendensi kepada nilai-nilai kebaikan. Aspek-aspek yang terbungkus pada karya sastra pada umumnya adalah aspek humanitas, sosial, intelektual, ataupun lainnya, yang disampaikan dengan redaksi yang khas.
Palto memberikan definisi yang ciamik mengenai sastra, yaitu hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan. Sebuah karya sastra merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan.sastra dapat digolongan menjadi dua jenis yaitu yang bersifat imajinatif dan non-imajinatif. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis karya sastra, antara lain puisi, drama, prosa, dan essai (Emzir, dkk, Tentang Sastra: Orkestrasi Teori dan Pembelajarannya, 4).
Ayat-Ayat Tentang Sastra
Ayat tentang sastra termaktub salah satunya dalam QS. al-Syuara’: 224-227, yang dibahasakan Al-Qur’an dengan seorang penyair:
وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۗاِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ
اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۙ
وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۙ
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗوَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ࣖ
“Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur’an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas, Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.”
Secara redaksional, ayat tersebut memberikan gambaran mengenai sastrawan dan karya sastranya. Kecuali dengan keimanan yang kokoh, seorang sastrawan dengan kemampuan olah-bahasa yang mumpuni akan menggiring pemahaman umat ke dalam kesesatan dan kehinaan.
Dalam redaksi suatu hadits disebutkan, dalam ayat tersebut juga mencitrakan ketidaksimpatikan al-Qur’an terhadap karya sastra yang ada. Dalam redaksi suatu hadits yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan;
“Seorang dari kamu lebih baik menelan nanah kemudian dimuntahkan kembali daripada menelan puisi”
Secara tegas, Nabi mengatakan bahwa sastra atau puisi, tidak lebih baik dari pada muntahan manusia. jika dipahami secara tekstual, hadits tersebut sangat menolak perkembangan puisi ataupun sastra pada masanya. Dalam QS. Yaasin: 69:
وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۗاِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur’an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas,
Keadaan Sastra Saat Al-Qur’an Datang
Pada masa pra-Islam, di Arab sastra menjadi salah satu pioner peradaban. Bahkan terdapat forum khusus untuk mempublikasi dan mendemonstrasikan karya-karya sastranya yang berbentuk puisi, prosa, atau yang lain. Terdapat ayyam al-asywaq, yaitu jadwal rutin pagelaran sastra di pasar Arab. Akan tetapi, turunnya Al-Qur’an menandakan lemahnya sastra. Nilai-nilai estetis yang terkandung dalam narasi sastra tereliminasi oleh keindahan kata, rima, dan irama, dalam Al-Qur’an.
Fenomena tersebut, diinterpretasikan oleh beberapa kalangan dengan justifikasi negatif terhadap sastra, yaitu sastra tidak ciamik lagi, karena tergerus oleh estetika bahasa Al-Qur’an. Ditambahi dengan QS. al-Syu’ara yang menyatakan ketidaksimpatikannya terhadap sastra. Sebab berpotensi merusak tatanan keimanan umat pada masa itu, yaitu dengan salah satu jenis konten sastra yang sifatnya mencela dan menghujat.
Dengan adanya redaksi al-Qur’an dan hadits yang secara zahir merendahkan para penyair, maka hal tersebut menjadi problematika tersendiri bagi kalangan ulama’ fikih perihal kebolehan syair atau sastra.
Bagaimana Fikih Memandang Sastra?
Jika kita merujuk pada kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa segala perkata tergentung niat dan maksudnya. Agaknya, hal itu bisa dijadikan instrumen untuk mampu menghukumi sastra secara fikih. Dalam tataran ayat yang telah disampaikan pada awal pembahasan, bahwa secara redaksional Al-Qur’an mencela para penyair atau sastrawan. Begitu juga dalam hadits, yang merendahkan syair dibandingkan dengan muntahan manusia.
Perdebatan mengenai seni dan sastra belum menemukan titik akhir. Bagi kalangan yang menolak kehadiran sastra, berdalih dengan dalil naqly yang tersurat dalam AL-Qur’an. Akan tetapi, Kalanga kontekstualis tidak menyempitkan maknanya sehingga terikat dengan teks kebahasaan yang ada. Ayat-ayat yang telah penulis paparkan di atas merupakan penegasan tentang sikap Al-Qur’an terhadap syair dan sastra.
Al-Qur’an menginginkan sastra bersifat membangun, bukan menjatuhkan dan menghujat. Islam, yang terkandung dalam nilai-nilai Al-Qur’an, menginginkan syair menyesuaikan diri dengan komunitas baru yang mengandung nilai-nilai luhur di dalamnya. Maka dari itu,sikap Islam terhadap sastra bukanlah musuh, akan tetapi pen-tashih syair dan sastra, serta meluruskan dari noda-noda kemungkaran (Wildana Wargadinata dan Laily Fitrianil, Sastra Arab: Masa Jahiliyah dan Islam, 12).
Dalam realitas kehidupan ulama Islam, Imam Syafi’i, yang pada dasarnya seorang ulama’ fiqh, juga dipandang sebagai seorang sastrawan. Sebagian berpendapat, bahwa beliau merupakan seorang kritikus sastra yang sangat disegani seirama (Muhammad al-Mubassyir, Berguru Kepada Ulama’, 12). Dari realitas tersebut bisa diinterpretasikan bahwa Imam Syafi’i, yang merupakan ulama fikih, juga konsep kepada sastra pada masa itu, sastra dan fikih bisa berjalan berbarengan.
Kesimpulan
Kembali kepada ushul fiqh, bahwa segala perkara kembali ke niatnya, maka begitupun dengan sastra. Jika dijadikan sebagai ajang mencela maka hukumnya haram, jika sebagai motivasi dan pembangunan umat, maka hukumnya halal.
Editor: Soleh
Desain Rumah Kabin
Rumah Kabin Kontena
Harga Rumah Kabin
Kos Rumah Kontena
Rumah Kabin 2 Tingkat
Rumah Kabin Panas
Rumah Kabin Murah
Sewa Rumah Kabin
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin
Source link